- 5 January 2026
- 4 min read

INDOWORK.ID, JAKARTA: Di tengah negeri yang kalau dengar kata hukum sering refleks menoleh ke belakang bukan karena takut salah, tapi takut disalahkan, Pandji Pragiwaksono datang membawa sebuah judul yang terdengar berat: “Mens Rea.” Istilah hukum Latin yang biasanya nongol di ruang sidang, bukan di panggung komedi. Tapi justru di situlah lelucon dimulai.
“Mens Rea” (2025) bukan sekadar spesial stand-up berdurasi 2 jam 24 menit yang tayang di Netflix pada 27 Desember 2025. Ini lebih mirip seperti ruang kelas alternatif, di mana dosennya bercanda, mahasiswanya tertawa, tapi pulangnya membawa PR bernama kesadaran. Diselenggarakan di Indonesia Arena, Jakarta, 30 Agustus 2025, acara ini terasa megah, tapi isinya sangat membumi membahas hal-hal yang sering kita keluhkan sambil ngopi, tapi jarang kita renungkan sambil berpikir.
Pandji mengajak penonton menelusuri budaya hukum Indonesia dengan gaya khasnya: santai, tajam, dan penuh jebakan logika yang bikin ketawa dulu, baru sadar kemudian. Ia bicara soal korupsi bukan seperti jaksa, tapi seperti teman lama yang capek menjelaskan hal yang sama berulang kali, dengan nada, “Sebenernya ini tuh simpel, tapi kok ya…”
Yang bikin “Mens Rea” jadi spesial dan mungkin agak bikin beberapa orang keringat dingin adalah kolaborasi resminya dengan KPK. Iya, lembaga yang biasanya identik dengan konferensi pers serius dan rompi oranye, kali ini memilih panggung komedi sebagai medium edukasi publik. Uniknya, tanpa sensor. Pandji dibiarkan menembak ke mana saja, selama pelurunya bernama fakta dan pengalaman sehari-hari.
TUJUANNYA REALISTIS

Tujuannya pun realistis. Bukan berharap penonton langsung jadi malaikat anti korupsi keesokan harinya. Tapi minimal, ada rasa tertampar. Rasa tidak nyaman yang sehat. Karena perubahan besar seringkali dimulai dari kalimat sederhana: “Oh… iya juga ya.”
Di situ Pandji menyebut nama. Dan ia tidak berbisik.
Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka, Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, Ferdy Sambo, Tedy Minahasa, bahkan Rafi Ahmad semua hadir bukan sebagai tokoh suci atau penjahat tunggal, tapi sebagai simbol dari sistem, kekuasaan, dan cara kita memaknainya. Bahkan Harris Azhar muncul sebagai penanda bahwa kritik di negeri ini kadang perlu “tips bertahan hidup”. Humor Pandji bekerja seperti pisau dapur, tidak terlihat mewah, tapi tajam dan sering mengenai jari sendiri.
Namun sasaran utamanya bukan cuma para elite.
Pandji justru lebih sering menoleh ke arah penonton ke arah kita. Ke warga Bogor yang dua kali salah pilih bupati. Ke Bandung yang tergoda popularitas artis. Ke pemilih yang datang ke TPS dengan semangat, tapi pulang tanpa benar-benar tahu siapa yang dicoblos. Di sini, sarkasmenya halus tapi kejam, “Kalau kita malas cari tahu, jangan heran kalau yang terpilih juga malas kerja.”
Respons publik pun beragam, sebagaimana seharusnya sebuah karya satir bekerja.
Banyak yang memuji “Mens Rea” sebagai edukasi politik yang tidak menggurui, materi berat yang bisa dicerna tanpa kamus hukum di tangan. Pandji dinilai piawai mengemas isu kompleks menjadi lelucon yang dekat dengan realita soal birokrasi, kekuasaan, dan kebiasaan kecil yang diam-diam memelihara sistem besar yang kita kutuk bersama.
“Mens Rea” pada akhirnya bukan soal Pandji ingin terlihat paling benar, atau KPK ingin terlihat paling progresif. Ini soal sebuah eksperimen sosial: bisakah komedi membuat kita berpikir tanpa merasa digurui? Bisakah tawa menjadi pintu masuk refleksi, bukan sekadar pelarian?
BUKAN SOLUSI INSTAN
Di ujung pertunjukan, “Mens Rea” tidak menawarkan solusi instan. Tidak ada janji perubahan besar besok pagi. Yang ada hanyalah harapan kecil bahwa setelah tertawa, penonton pulang dengan satu pertanyaan mengganggu di kepala:
“Selama ini, niat kita sebagai warga negara sebenarnya apa?”
“Mens Rea” akhirnya terasa seperti cermin besar yang dipasang di tengah arena. Kita tertawa melihat pantulan orang lain,politisi, pejabat, sistem. Sampai di satu titik, kita sadar yang ada di dalam cermin itu juga kita. Dengan pilihan-pilihan kecil kita. Dengan sikap permisif kita. Dengan kebiasaan kita menormalisasi hal-hal yang seharusnya tidak normal.
Dan mungkin, di situlah kekuatan sebenarnya dari spesial ini. Bukan pada siapa yang disindir, tapi pada siapa yang pulang dengan perasaan sedikit terusik. Karena perubahan, seperti kata hukum yang jadi judulnya, selalu dimulai dari niat. Dari mens rea. Dari isi kepala.
*) Ditulis oleh Andrian Saputra, aktivis media sosial





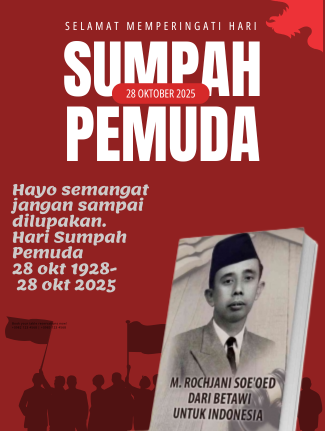





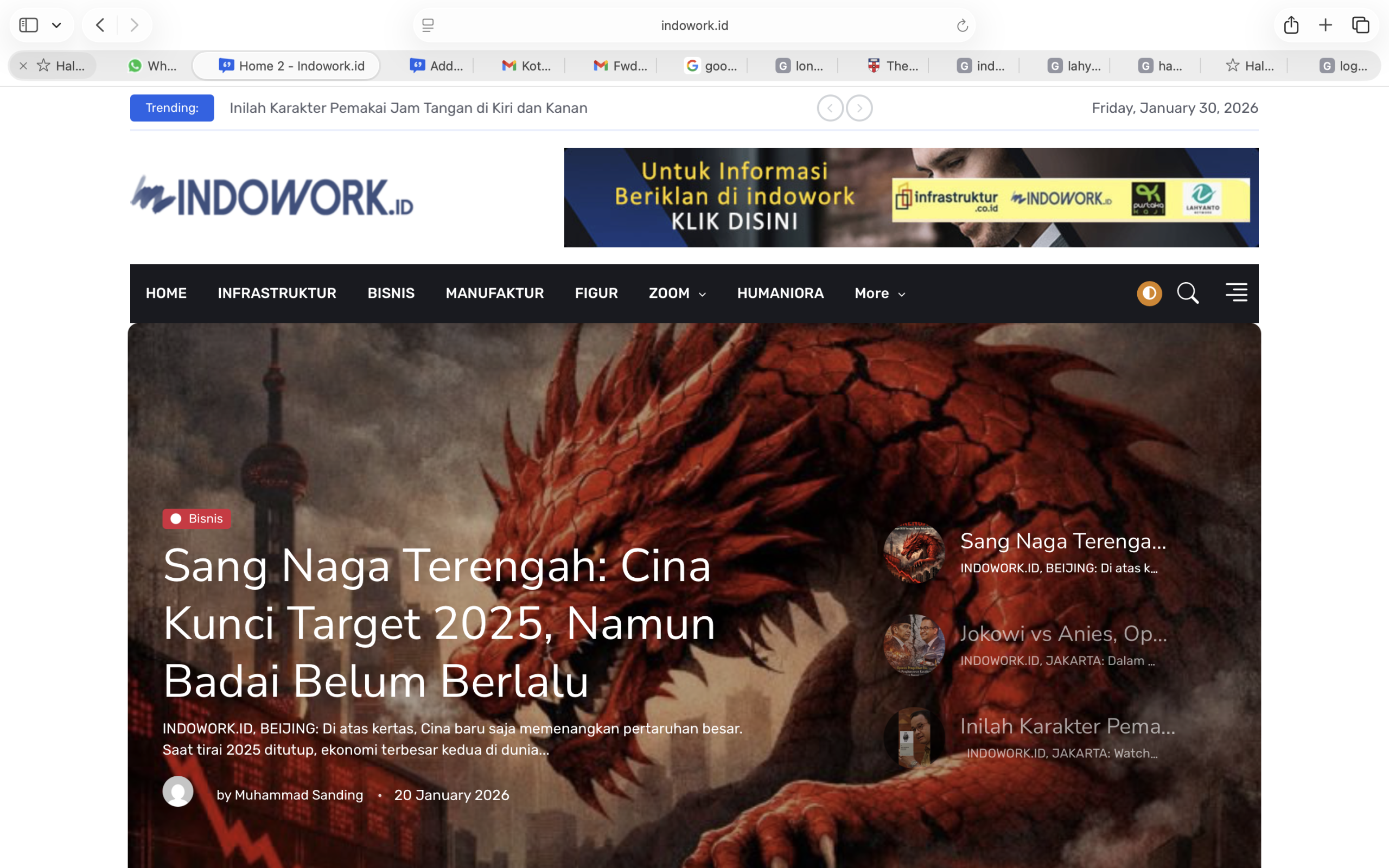


Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *