
INDOWORK.ID, JAKARTA: Pembekuan sementara penggunaan sirene dan strobo oleh Kepolisian pekan ini bukan sekadar soal teknis lalu lintas. Ia menyentuh jantung relasi antara pejabat publik dan warganya.
Sirene yang melengking, klakson “tot tot wuk wuk” yang membelah jalanan, dan iring-iringan mobil berlampu strobo telah lama menjadi simbol kekuasaan di jalan raya.
Masalahnya, di mata masyarakat, simbol itu kerap terasa arogan. Ia menciptakan kesan bahwa jalan raya milik pejabat, sementara rakyat hanya penonton yang wajib menepi. Tak heran jika keluhan demi keluhan muncul, hingga akhirnya polisi merasa perlu melakukan evaluasi.
Jika menengok ke luar negeri, pola pengawalan pejabat menunjukkan wajah yang beragam. Di Amerika Serikat, pengawalan Presiden adalah operasi militer kecil: mobil lapis baja, motor, sniper, dan Secret Service yang tak pernah lengah. Begitu pula di
Rusia atau Tiongkok, di mana pengawalan besar-besaran menjadi simbol kekuasaan negara.
Namun di Skandinavia—Swedia, Norwegia, Denmark, Finlandia—gambarannya lain. Perdana Menteri atau Raja sering terlihat berjalan santai di ruang publik dengan pengawalan minimal, kadang hanya petugas berpakaian sipil yang menjaga jarak. Keamanan tetap ada, tetapi tanpa seremonial berlebihan.
FILOSOFI POLITIK
Perbedaan ini mencerminkan filosofi politik. Di negara demokrasi mapan, pengawalan diposisikan sebagai alat darurat, bukan atribut kewibawaan. Sirene dipakai hanya ketika benar-benar dibutuhkan—misalnya darurat medis atau ancaman nyata.
Polemik penggunaan sirene dan strobo bagi kendaraan pejabat di Indonesia kembali mencuat setelah Kepolisian membekukan sementara penggunaannya. Langkah ini menyoroti pertanyaan mendasar: seberapa perlu pengawalan di jalan raya, dan bagaimana praktik serupa dijalankan di negara lain?
Di banyak negara, pola pengawalan pejabat sangat ditentukan oleh tingkat ancaman keamanan, budaya politik, dan aturan protokoler.
Di Negeri Paman Sam, Presiden dan Wakil Presiden hampir tak pernah terlihat di ruang publik tanpa kawalan ketat. Secret Service mengatur segalanya: dari kendaraan lapis baja, iring-iringan motor, hingga sniper tersembunyi. Bahkan menteri-menteri strategis seperti Menteri Luar Negeri, Pertahanan, dan Keuangan turut mendapat perlakuan serupa. Namun anggota kongres atau pejabat parlemen biasanya hanya dilindungi secara minimal.
Perdana Menteri Inggris dikawal Protection Command, unit elite dari Metropolitan Police. Keluarga Kerajaan pun mendapat perlindungan ekstra dari Royalty and Specialist Protection. Namun menariknya, menteri kabinet tidak selalu dikawal di jalan raya kecuali menghadapi ancaman serius.
Di Prancis, Presiden dilindungi Groupe de Sécurité de la Présidence de la République (GSPR) dengan iring-iringan besar. Perdana Menteri dan Menteri Dalam Negeri juga dikawal ketat. Pola serupa berlaku di Jerman, di mana Kanselir dan Presiden Federal selalu berada dalam pengawalan Bundeskriminalamt (BKA), sementara menteri lain dilindungi lebih fleksibel sesuai kebutuhan.
Di Jepang, Kaisar dan keluarga kekaisaran mendapat pengamanan ekstrem, sementara Perdana Menteri juga selalu dikawal polisi khusus. Namun menteri lain biasanya hanya dikawal saat acara resmi.
Berbeda dengan negara besar, di Norwegia, Swedia, Denmark, dan Finlandia, pejabat tinggi sering terlihat berjalan santai dengan pengawalan minim. Perdana Menteri dan Raja/Ratu tetap dijaga, tapi secara sederhana, bahkan kadang dengan petugas berpakaian sipil. Transparansi publik dianggap lebih penting dibanding iring-iringan panjang di jalan raya.
WAJAH BERBEDA
Negara dengan risiko tinggi keamanan menampilkan wajah berbeda. Presiden Rusia, Vladimir Putin, misalnya, dikawal ketat Federal Protective Service (FSO) dengan sistem keamanan berlapis. Di Tiongkok, Xi Jinping dilindungi Central Security Bureau. Iring-iringan besar, motor, hingga pasukan bersenjata adalah pemandangan lumrah di kawasan ini.
Perbandingan ini menunjukkan pola umum: kepala negara atau kepala pemerintahan selalu dikawal ketat, sementara menteri dan pejabat lain hanya dilindungi sesuai kebutuhan.
Konteks Indonesia saat ini menarik. Keputusan Korlantas Polri menghentikan sementara penggunaan sirene—yang kerap dikeluhkan publik karena mengganggu lalu lintas—sejalan dengan praktik internasional. Di negara-negara demokrasi mapan, sirene bukan simbol kekuasaan, melainkan alat darurat yang dipakai secara selektif.
Langkah evaluasi yang diambil Polri dapat menjadi momentum penting untuk menata ulang tata cara pengawalan pejabat di jalan raya. Pada akhirnya, pengawalan memang soal keamanan, tetapi cara penyajiannya di ruang publik akan selalu merefleksikan wajah negara: apakah mengedepankan kewibawaan atau justru keterbukaan.
Keputusan Polri membekukan sementara penggunaan sirene patut diapresiasi. Tapi lebih penting lagi, evaluasi ini mesti menjawab pertanyaan mendasar: apakah sirene akan terus dipandang sebagai hak istimewa pejabat, ataukah dikembalikan ke fungsi semula sebagai alat prioritas dalam kondisi darurat?

Setiap iring-iringan pejabat sejatinya adalah panggung kecil tentang bagaimana negara memperlakukan rakyatnya. Apakah negara hadir dengan wajah egaliter, ataukah dengan wajah yang minta didahulukan?
Pada akhirnya, sirene dan strobo bukanlah sekadar peralatan lalu lintas. Ia adalah simbol. Jika digunakan dengan bijak, ia melindungi. Jika dipakai sembarangan, ia merusak legitimasi.
Indonesia kini punya peluang untuk memilih simbol mana yang ingin ditampilkan: negara yang kuat tapi dekat dengan rakyat, atau negara yang keras tapi terasa jauh dari rakyatnya?
*) Ditulis oleh Deddy H. Pakpahan, wartawan senior.





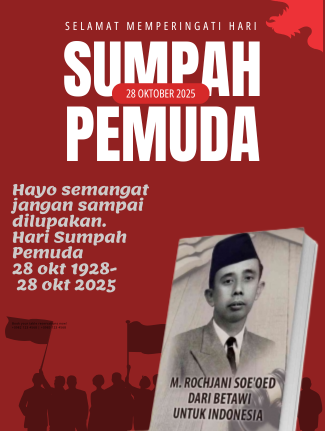




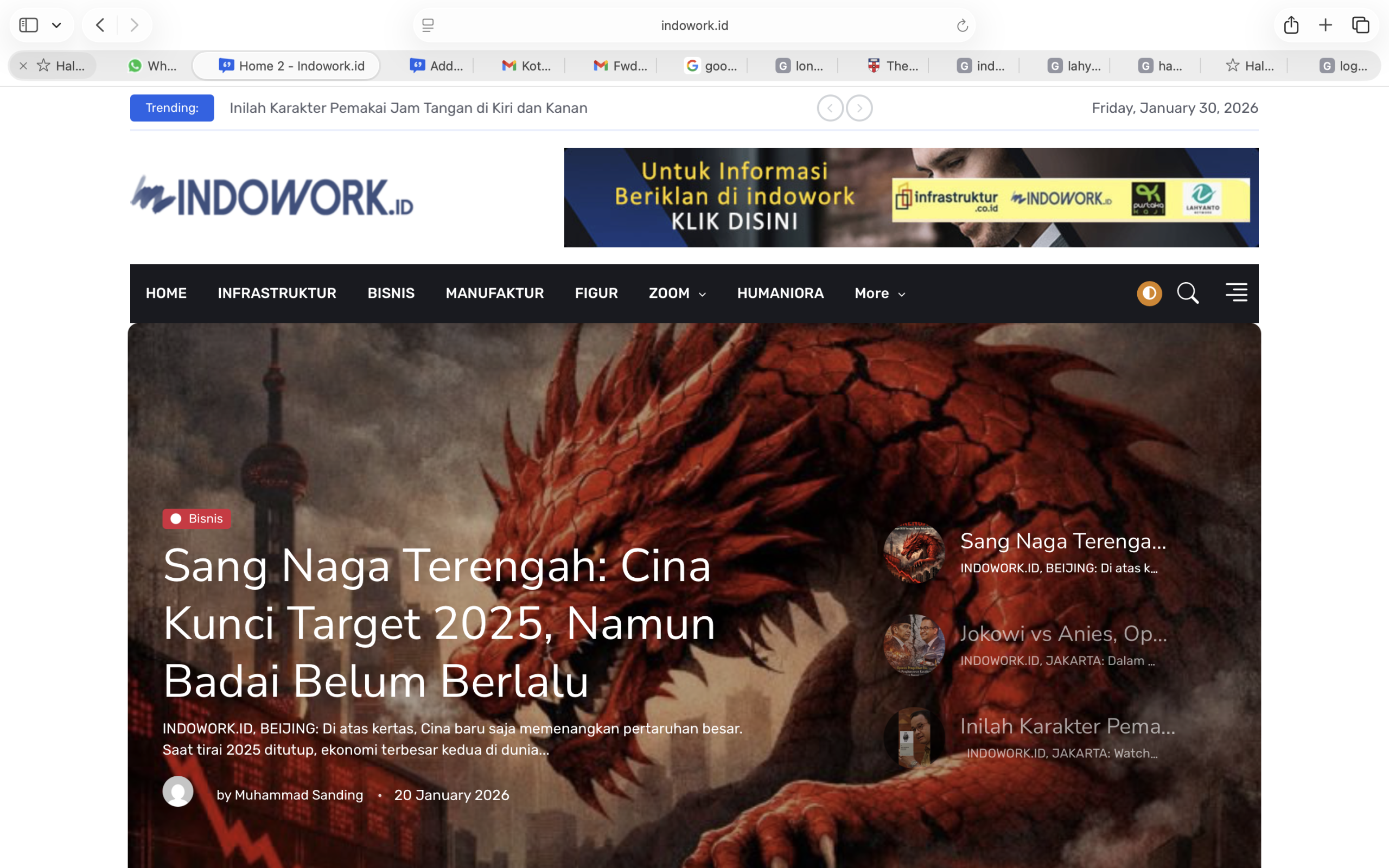



Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *