- 31 December 2025
- 6 min read

INDOWORK.ID, JAKARTA: Catatan Akhir Tahun Dewan Pers 2025 kubaca pelan, bukan karena bahasanya sulit, melainkan karena ada rasa getir yang akrab. Seperti membaca laporan kesehatan seorang sahabat lama yang kita tahu sedang sakit, tapi terus bersikap seolah cukup minum vitamin.
Sebagai pensiunan wartawan, aku punya utang emosional pada pers. Aku dibesarkan oleh ruang redaksi yang ribut, idealisme yang naif, dan keyakinan bahwa kebenaran, meski sering kalah cepat, pada akhirnya akan menemukan jalannya.
Maka ketika Dewan Pers kembali membunyikan alarm tentang kemerdekaan pers, profesionalisme, dan ekonomi media, aku mengangguk. Tapi anggukan ini bukan tanda setuju sepenuhnya. Lebih mirip gerakan kepala orang tua yang berkata: iya, tapi kenapa baru di situ lagi.
Catatan Dewan Pers sebagai refleksi tahun 2025 jujur menyebut ancaman kemerdekaan pers yang nyata. Perampasan dan penghapusan rekaman wartawan Kompas TV di Aceh, penghapusan konten CNN Indonesia, tekanan verbal dari pejabat.
Semua itu bukan anomali. Ia pola. Dalam teori chilling effect yang dibahas Vincent Blasi, kekuasaan tak perlu selalu menutup media secara resmi. Cukup ciptakan rasa takut, maka sensor akan bekerja dengan sendirinya. Ketika redaksi mulai bertanya, “aman nggak ya ini tayang?”, negara sebenarnya sudah menang setengah langkah.
SOROTI KEKURANGAN

Dewan Pers menegur pernyataan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang meminta media “tidak terlalu menyoroti kekurangan pemerintah”.
Di atas kertas, Dewan Pers benar. Tapi sebagai orang yang pernah duduk di ruang redaksi, aku tahu persoalannya lebih dalam. Di banyak meja redaksi hari ini, tekanan paling efektif bukan lagi ancaman langsung pejabat, melainkan kombinasi akses, iklan, dan algoritma.
Media yang terlalu keras bisa kehilangan narasumber, iklan, bahkan jangkauan digital. Pierre Bourdieu menyebut ini sebagai tekanan medan (field) yang membuat aktor menyesuaikan diri demi bertahan hidup.
Ketika Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat mengutip Pasal 4 ayat (3) UU Pers, aku menghargainya. Tapi hukum, seperti payung di tengah badai, hanya menutupi kepala, bukan tubuh.
Kekerasan terhadap wartawan tetap terjadi. Dari pemukulan jurnalis Antara, pengeroyokan di Banten, sampai teror kepala babi dan bangkai tikus ke wartawan Tempo. Ini bukan sekadar kriminalitas. Ini pesan simbolik. Dalam kajian komunikasi politik, teror simbolik bertujuan menciptakan ketakutan kolektif, bukan sekadar melukai individu.
Gugatan Rp200 miliar oleh Amran Sulaiman terhadap Tempo memperlihatkan bentuk lain dari tekanan. Bukan borgol, tapi amplop gugatan. Bukan pentungan, tapi biaya hukum.
Lawrence Lessig pernah menulis tentang bagaimana hukum bisa dipakai sebagai senjata regulatif untuk membungkam, bukan melindungi. Strategic Lawsuit Against Public Participation, atau SLAPP, bekerja dengan logika sederhana: bikin capek, bikin mahal, bikin takut.
Data Indeks Kemerdekaan Pers yang stagnan di angka “cukup bebas” seharusnya membuat kita berhenti bertepuk tangan. “Cukup bebas” itu bahasa birokrasi untuk mengatakan: belum aman. Dewan Pers menyebut rasa tidak aman mendorong swa-sensor.
MENEKAN PEMERINTAH
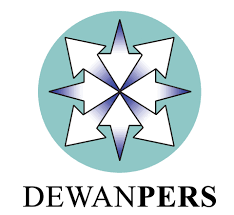
Benar. Tapi lagi-lagi, aku ingin bertanya dengan nada yang mungkin terdengar kurang sopan: sejauh mana Dewan Pers berani menekan pemerintah, bukan sekadar mengingatkan?
Upaya perlindungan hukum melalui penyediaan ahli pers patut diapresiasi. Mekanisme Nasional Keselamatan Pers juga langkah maju. Dalam teori institusionalisme baru, ini disebut upaya membangun “protective institution” agar norma kebebasan pers punya penopang struktural. Tapi institusi tanpa gigi hanya akan menjadi brosur kebijakan.
Satgas akan diuji bukan saat konferensi pers, melainkan saat aparat di lapangan menampar wartawan, atau saat gugatan raksasa diajukan oleh pejabat.
Di sisi lain, lonjakan pengaduan publik ke Dewan Pers menunjukkan paradoks. Publik makin kritis pada media, tapi kepercayaan pada media justru rapuh. Banyak aduan soal clickbait, pelanggaran cover both sides, dan ujaran kebencian. Ini bukan sekadar kesalahan individu wartawan. Ini hasil dari ekonomi atensi.
Dalam kerangka attention economy ala Herbert Simon, perhatian adalah sumber daya langka. Media yang lapar iklan akan mengejar klik, bahkan jika itu berarti mengorbankan etika.
Dewan Pers merespons dengan UKW dan pedoman AI. Secara normatif, ini baik. Tapi pengalaman mengajarkanku satu hal pahit, sertifikat tidak otomatis melahirkan keberanian. UKW bisa memastikan kompetensi teknis, tapi tidak menjamin keberanian editorial ketika berhadapan dengan pemilik modal atau tekanan politik.
Pedoman AI pun penting, tapi di ruang redaksi yang kekurangan orang dan dikejar target, AI sering diperlakukan sebagai jalan pintas, bukan alat etis.
Tekanan ekonomi media adalah luka terbuka. Data Aliansi Jurnalis Independen tentang ratusan PHK hanyalah puncak gunung es. Banyak redaksi hidup dengan gaji terlambat, kontrak tak jelas, dan jam kerja tak manusiawi.
Dalam kondisi seperti ini, idealisme sering menjadi kemewahan. Teori precarious labor menjelaskan bagaimana pekerja yang rentan secara ekonomi cenderung menghindari risiko. Jurnalis yang takut kehilangan pekerjaan akan berpikir dua kali sebelum menulis laporan investigatif.
Inisiatif Dana Jurnalisme Indonesia, revisi UU Hak Cipta, dan kerja sama dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah langkah strategis. Tapi aku curiga pada satu hal: apakah Dewan Pers sudah cukup keras menuntut tanggung jawab platform digital global?
Selama ini, banyak dialog terasa terlalu sopan, terlalu diplomatis. Padahal relasi media dan platform adalah relasi timpang. Tanpa keberanian politik, media lokal akan terus menjadi pemasok konten murah bagi algoritma mahal.
PENGHARGAAN

Di bagian penutup, Dewan Pers menganugerahkan penghargaan pada Jusuf Kalla, almarhum Jakob Oetama, dan wartawan tangguh. Penghargaan ini pantas. Jakob Oetama adalah pengingat bahwa pers pernah dijalankan dengan kesabaran, kedalaman, dan keberanian moral. Tapi justru di sini ironi itu terasa. Kita merayakan figur masa lalu karena hari ini kita kekurangan teladan yang sama kuatnya.
Sebagai pensiunan wartawan, kritikku pada Dewan Pers sederhana tapi tidak ringan. Dewan Pers terlalu sering berdiri sebagai penengah yang santun, padahal situasi menuntut sikap lebih konfrontatif.
Dalam teori peran lembaga penyangga demokrasi, ada saatnya mediator berubah menjadi advokat publik. Bukan sekadar mengeluarkan pernyataan, tapi memaksa perubahan melalui tekanan politik, opini publik, dan keberpihakan yang jelas.
Aku paham, Dewan Pers bekerja di ruang yang penuh kompromi. Tapi sejarah pers mengajarkan satu hal: kebebasan tidak pernah diberikan, ia direbut dan dipertahankan.

Jika Dewan Pers ingin lebih dari sekadar pencatat krisis, ia harus berani mengambil risiko reputasional dan politik. Jika tidak, alarm akan terus berbunyi setiap akhir tahun, sementara rumahnya perlahan terbakar.
Kututup senandika ini sambil berharap industri pers kita masih terus ada. Belum mati. Tapi jelas butuh api baru, bukan hanya laporan tahunan, untuk kembali hangat dan hidup.
*) Ditulis oleh Wicaksono, wartawan senior.





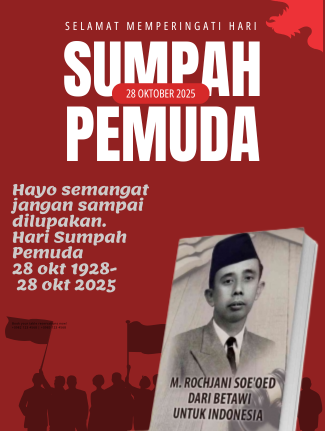






Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *