INDOWORK.ID, JAKARTA: Saya menyimak pernyataan keprihatinan Bung Bahrul Alam, jurnalis senior di laman FB-nya, kemarin (Jumat, 19 September 2025) sebagai curahan hati yang juga saya rasakan.
Kami sam- sama jurnalis yang aktif di era ketika sebuah berita melewati meja redaktur, diedit ketat, diverifikasi, sebelum ditayangkan. Kami sama sama rutin rapat redaksi untuk membahas informasi apa yang akan disiarkan. Dan kini segala macam berita bebas tayang tanpa hambatan.
Apa yang disampaikan ‘al ustadz jurnalisme’ Bahrul Alam itu – dalam seni karawitan Jawa, merupakan “bawa/bowo” atau “prelude” di musik klasik atau “overture” dalam pertunjukkan opera. Lantunan vokal tunggal yang pembuka – sebelum diiringi oleh instrument lengkap.
Izinkan saya menyusun aransmen lagu dan musik selengkapnya – elaborasi dari ‘bawa/bowo’ yang dibawakan oleh ‘Almukarom’ Bahrul Alam – yang di era kejayaan RCTI beliau kita kenal program Seputar Indonesia dengan berita-berita aktualnya.
Pada hari ini, Sabtu, 20 September 2025, setelah sama-sama pensiun dari media arus utama itu – kami melewati hari-hari yang menyaksikan bukan lagi terjadi banjir berita, melainkan banjir informasi – setara tsunami. Banjir bandang yang bukan membawa pencerahan, melainkan menghanyutkan akal sehat.
DAHULU ADA GATEKEEPER
Dahulu, ada yang namanya gatekeeper. Jurnalis memilih sumber kredibel kompeten dan memastikan informasi yang diperoleh valid, hanya fakta yang lolos ke mata publik. Kini? Gatekeeper sudah pensiun dini, digantikan algoritma media sosial yang lebih peduli pada jumlah ‘like’ daripada kebenaran.
Neil Postman (1931 – 2003), kritikus budaya Amerika – yang menghindari teknologi digital – barangkali akan tertawa getir jika melihat ramalannya terbukti: kita tenggelam dalam banjir informasi yang ironisnya melahirkan kelangkaan kebenaran. Di era ini, setiap orang adalah penyiar, reporter, sekaligus redakturnya sendiri.
Apa yang dikhawatirkan Clay Shirky, 61, pakar media dan konsultan Amerika – tentang dampak sosial dan ekonomi teknologi Internet dan jurnalisme – boleh jadi benar: “penerbitan dulunya adalah sebuah industri, kini tinggal tombol” (‘publishing used to be an industry, now it’s a button’). Tekan tombol, sebarkan rumor, lalu biarkan masyarakat menelannya mentah-mentah.
Tak perlu cek ricek, validasi, tak perlu sensor moral, apalagi kode etik. Mengapa? Karena semua orang merasa punya hak bersuara, meski tak semua punya kapasitas untuk tidak berbohong.
DIPUJA SEOLAH DEWA
Sementara itu, jurnalisme warga dipuja-puji seolah dewa penyelamat demokrasi. Padahal, seringkali yang lahir hanyalah gosip, kemarahan, atau teori konspirasi setengah matang.
Akhirnya kita sedang menyaksikan fondasi demokrasi dikikis oleh status Facebook dan thread X/Twitter yang viral.
Ironis, kan? Demokrasi yang dulu dibela dengan darah dan air mata, kini digadaikan dengan ‘retweet’ murahan.
Lalau – datang lagi – teknologi terbaru: kecerdasan buatan. ‘Artificial intelligence’ (AI) yang mampu menulis berita palsu yang terdengar lebih meyakinkan daripada laporan investigasi seorang jurnalis berpengalaman. Lebih parah lagi, Deepfake bisa memalsukan wajah pemimpin, suara tokoh, bahkan menciptakan saksi palsu yang tak pernah ada.
Bayangkan saja, pidato Menteri Keuangan dipalsukan A.I., seolah-olah Sri Mulyani mengucapkan “Guru adalah beban negara” – beredar begitu cepat, lengkap dengan mimik wajah dan intonasi suara yang nyaris sempurna. Publik yang sudah frustrasi langsung tertipu – dan tersulut. Amarah digital menjelma jadi amarah jalanan. Rumah sang Menteri pun diserbu dan dijarah. Bukan karena kebijakan nyata, melainkan karena manipulasi teknologi.
Shoshana Zuboff , profesor, psikolog sosial, penulis buku In the Age of the Smart Machine: The Future of Work and Power – studi khusus tentang teknologi informasi di tempat kerja – sudah mengingatkan: teknologi tidak netral, ia dikendalikan oleh kepentingan ekonomi dan politik. Maka, jangan heran, jika AI lebih sering dipakai untuk propaganda ketimbang pencerdasan.
Dan kita semua kini hidup di dunia di mana sebuah “pidato palsu” bisa berujung pada kerusuhan nyata.
Masalahnya – bukan hanya teknologinya, tapi juga manusia yang begitu mudah diperdaya. Psikolog menyebutnya sebagai “efek ilusi kebenaran” (illusion of truth effect) di mana semakin sering sebuah hoaks diulang, semakin dianggap benar.
Inilah tragedi kita: di tengah lautan informasi, masyarakat justru kehilangan kompas. Mereka lebih percaya kabar dari X/Twitter, grup WhatsApp (WAG) keluarga ketimbang laporan panjang media nasional.
DOSA MEDIA ARUS UTAMA
Apakah media arus utama tak punya dosa? Tentu punya. Ada media yang tergoda kecepatan, mengorbankan ketelitian. Ada yang jadi corong kekuasaan. Tapi setidaknya, masih ada kode etik, redaksi, dan mekanisme koreksi. Ada alamat kantor yang bisa dituju untuk menggugat.
Bandingkan dengan akun anonim penyebar rumor—siapa yang mau Anda tuntut? Avatar kucing?
Demokrasi yang sehat membutuhkan informasi yang sahih, tetapi demokrasi kita kini berjalan di atas fondasi emosi yang dibakar algoritma.
Denis McQuail dalam buku Teori Komunikasi Massa menyebut media sebagai pilar keempat demokrasi. Sekarang, pilar itu nyaris keropos, digantikan pasar bisik-bisik digital. Publik lebih percaya kabar bohong yang sensasional ketimbang laporan investigasi yang memerlukan bulan kerja keras.

Apa jalan keluarnya? Bukan dengan menolak teknologi, tentu. Tapi dengan merehabilitasi martabat jurnalisme: menegaskan kembali etika, moral, transparansi, dan tanggung jawab.
Media harus kembali ke akar: bukan sekadar cepat, tapi benar.
Bukan sekadar viral, tapi bermakna. Bukan begitu Al Mukarom Al Ustadz Haji Bahrul Alam ?
*) Ditulis olehDimas Supriyanto, wartawan senior.
CATATAN: Redaksi juga menunggu jawaban dari Bahrul Alam.


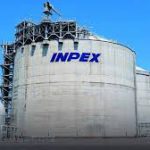


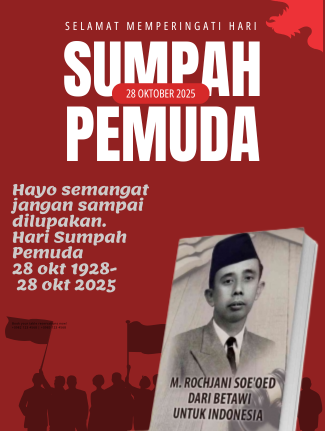



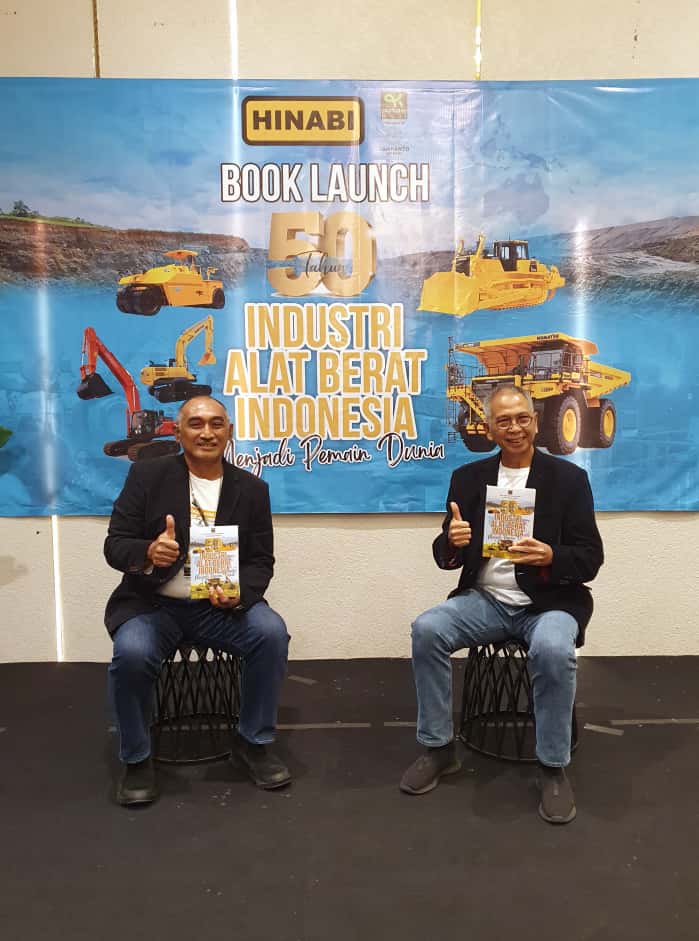
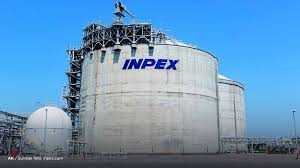




Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *