Cerite Jakarte: Kampung Sawah Sebelum Digusur untuk Kampus Universitas Indonesia

INDOWORK.ID, JAKARTA: Ketika keluarga kami pindah ke Kampung Sawah dari Gang Camat Gabun di Kampung Srengseng, Pada akhir 1969, sesungguhnya tak ada perbedaan nama kampung. Keduanya berada di wilayah Kelurahan Lenteng Agung, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan.
Namun pada 1970, Kelurahan Srengseng Sawah memisahkan diri, meskipun tetap di Kecamatan Pasar Minggu. Namun pada 1989, dibentuk kecamatan Jagakarsa sehingga, ia menjadi kelurahan Srengseng Sawah, bersama Lenteng Agung, Tanjung Barat, Ciganjur, dan Jagakarsa itu sendiri. Belakangan Kelurahan Cipedak memisahkan diri dari kelurahan Ciganjur.
Jauuh sebelumnya, Srengseng Sawah hingga 1930-an menjadi bagian dari wilayah Distrik (Kawedanan) Kebayoran. Asal usul nama Srengseng Sawah, menurut guru saya, Pak Minan Asan, yang bercerita ketika saya duduk di bangku kelas 5 Sekolah Dasar pada 1975, kata “srengseng” berasal dari akar kata “sereh” mengingat pohon sereh di kampung tersebut. Entah kapan, tersebutkan pembangunan pabrik minyak sereh yang atapnya terbuat dari “seng” yang letaknya di tengah sawah. Maka dinamakanlah Srengseng Sawah.
Asal-usul nama lain dijelaskan oleh Zaenuddin HM, dalam bukunya “212 Asal-Usul Djakarta Tempo Doeloe,” setebal 377 halaman, yang diterbitkan Ufuk Press pada Oktober 2012. Semula nama itu disebut Srengseng saja, tanpa kata Sawah di belakangnya. Sebab, dahulu orang-orang Belanda VOC menyebutnya Sringsing. Lantaran banyak dibuka persawahan, maka kemudian disebut Srengseng Sawah.
PANDAN BERDURI
Srengseng diambil dari nama semacam tanaman pandan berdaun lebar yang pinggirnya berduri-duri (Pandanus Caricosus Rmph), termasuk famili Pandaneseae, yang daunnya biasa dianyam menjadi tikar atau topi. Hingga meletus Perang Dunia ke-2, produksi tikar dan topi pandan dari kawasan itu mempunyai nilai ekonomis cukup berarti, hingga dipasarkan ke berbagai daerah lain, termasuk ke luar pulau Jawa. Sampai dengan 1970-an masih banyak penduduk asli Srengseng Sawah dan sekitarnya yang mebuat tikar dan topi pandan sebagai usaha sampingan.
Namun, juga disebutkan bahwa pada 1674 kawasan Srengseng Sawah tercatat sebagai milik Karim, anak seorang bekas kapten Jawa, bernama Citragladak. Kemudian, jatuh ke tangan Cornelis Chalestein, tuan tanah kaya raya yang antara lain memiliki tanah partikelir Depok.

Budayawan Betawi Ridwan Saidi ketika ceramah dalam acara maulid Nabi Muhammad SAW di masjid Al Ikhwan, pada 1995, juga bercerita tentang akar kata “sringsing” berasal dari bahasa Sunda Sansekerta yang berarti air yang bergericik. Sementara itu, Sofyan Murtadho (lurah Srengsengsawah 2000-2005) mengatakan bahwa kata “srengseg” berarti bentuk tanah tidak tidak beraturan. Ada yang tinggi, ada yang rendah dan berlegok-legok.
SEBRANG KULON DAN SEBRANG BETAN
Seingat saya, pada 1969 (ketika itu usia saya 5 tahun), sejak pindah ke Kampung Sawah, antara rumah Engkong saya Haji Maat bin Haji Sibi Radjimin dan rumah Wak Tuni, yang dikenal sebagai dukun beranak, tidaklah terlalu jauh. Namun demikian rumah Wak Tuni disebut sebagai Sebrang Kulon, sedangkan rumah engkong saya sebagai Sebrang Betan.
Mengapa saya cerita dukun beranak? Karena tokoh inilah yang menyatukan seluruh warga kampung. Setiap ada ibu yang melahirkan, pasti membutuhkan jasanya.
Dari penduduk setempatlah saya mengetahui bahwa lantaran dibatasi oleh Kali Srengseng, kedua tempat itu berbeda. Wilayah sebelah timur di mana tempat Engkong saya bermukim disebut sebagai Sebrang Betan oleh orang-orang Sebrang Kulon. Begitu pun sebaliknya. “Mao ke Sebrang Kulon nih nyari tukang buat bikin rumah,” begitu kata orang Sebrang Betan.
Pertama kali saya menginjakkan kaki ke Sebrang Kulon lantaran mengikuti Bapak saya yang mengantarkan buah tangan untuk Wak Tuni. Pada 21 April 1969, Emak saya melahirkan adik yang bernama Herlina.
Sebagai syaratnya Bapak membawakan hantaran berubah beras, lauk pauk, dan seekor ayam betina untuk Wak Tuni.
Sepanjang perjalanan Bapak tidak boleh bicara. Jika ada yang memanggil pun, Bapak tak boleh menyahut. Dasar teman-teman Bapak iseng, ada saja yang menggoda agar ia menyahuti panggilannya. Jika Bapak saya terpancing dan menyahut, niscaya ia harus pulang lagi ke rumah dan mengulanginya dari awal.
Bayangkan, Bapak harus jalan kaki di jalan yang kering di musim kemarau atau becek di musim penghujan, dari Kampung Srengseng ke Sebrang Kulon, sekitar 2 km.
Mengapa Wak Tuni diberikan hantaran? Itulah adat orang Betawi, khususnya orang Kampung Sawah dan sekitarnya. Jika Wak Tuni selesai membantu seorang ibu melahirkan, maka sebagai syarat tak tertulis, sang bapak memberikan hantaran itu.
Menurut Ali Munawar bin H. Mali, 70, di Sebrang Kulon bermukim tiga orang dukun beranak, yaitu Wak Tuni, Mak Djendil, dan Mpi Kaman.
Sementara itu, Samin bin Haji Arsjad Ma’an, 62, mengatakan bahwa selain ketiga dukun beranak itu juga ada Wak Amin yang tinggal di daerah Kalibata dekat asrama Yon Zikon 14. Hal itu dibenarkan oleh Yakub Marta (kini almarhum). “Benar itu, Wak Amin tinggal di situ menjadi tetangga saya. Sekarang dikenal sebagai Gang Boncel,” kata Yakub.
Roif Saih, 75, menjelaskan bahwa sebelumnya Wa Amin tinggal di Sebrang Kulon, dekat rumah Wak Sian dan Kong Ibrahim. Jika tinggal di Gang Boncel seperti yang dijelaskan Bang Haji Yakub, berarti ketika itu ia menetap di rumah anaknya yang bernama Saih Djeran.
Menurut Roif, dukun beranak yang paling senior adalah Nyai Kaman. “Wak Djendil itu muridnya Nyai Kaman.”
Selain berprofesi sebagai dukun beranak, warga Sebrang Kulon juga banyak tukang yang ahli membuat rumah. Sebut saja Wak Kitong, Bang Basar, Bang Sardjan, Cang Demit, dan Cang Saih. Yang terakhir ini adalah ayahnya Roif.
Makanya ketika perayaan 17 Agustusan, rombongan dari Sebrang Kulon paling keren. Di atas becak diaraklah miniatur rumah yang bagus karya para tukang itu. Di samping kerajinan tangan, orang Sebrang Kulon juga memamerkan hasil pertanian.
Singkong sebesar paha orang dewasa, pernah ditampilkan dalam perayaan Hari Kemerdekaan itu.
Sementara orang Sebrang Betan, selain produk pertanian juga pamer kemampua kesenian. Lenong Bang Main dan Orkes Permata pimpinan Cang Tarmuji adalah cerminan jiwa seni orang-orang Sebrang Betan.
Keistimewaan, kalau boleh disebut begitu, orang-rang Sebrang Betan adalah soal religiusitas. Boleh dibilang tokoh-tokoh agama banyak yang bermukim di sini, khususnya Bambon.
Perbedaan keduanya bukan memunculkan perpecahan, namun justru saling mengisi. Jika ada warga Kampung Betan mau melahirkan atau membuat rumah tentu membutuhkan saja orang sebrang Kulon. Begitu pun ketika akan ada perayaan hari-hari besar Islam seperti maulid atau isro mi’roj maka orag Sebrang Kulon yang mengundang orang Sebrang Betan untuk membacakan rawi.
Maka rombongan Haji Muhiddin, Haji Nasir, Haji Usman, Haji Muchtar, (semuanya anak Kong Haji Ali Bin Djamin bin Daud) bersama para imam dari Bambon yaitu Amil Totong dan Haji Abdullah bin H. Nean, beramai-ramai ke Sebrang Kulon.
ORGANISASI PERTAMA

Meski tanpa ada organisasi yang menyatukan, sesungguhnya secara budaya, adat, dan kerukunan orang-orang sebrang Betan dan Sebrang Kulon serupa dan seirama. Namun pada 3 Desember 1972, didirikanlah organasi yang menyatukan kampung tersebut yang dinamakan Ikatan Keluarga Kampung Sawah. (IKKAS)
Sesungguhnya yang hendak saya ceritakan adalah bukan hanya penduduk rumah yang ada di Sebrang Kulon. Sengaja tulis sebrang dengan lidah orang Kampung Sawah. Bahasa Indonesianya seberang yang berarti sisi di sebelah sana (baik untuk sungai, jalan, laut, dan sebagainya).
“Mao kondangan ke sebrang kulon,” kata orang Sebrang Betan.
Dari arah selatan seingat saya yang paling dekat dengan rel kereta api adalah rumah Kong H. Niung, jika ada keperluan saya ke sana bersama Emak dan Bapak. Ke arah utara sedikit ada rumah Cang Sairih bin H. Niih. Di depannya berdirilah SD Srengsengsawah III Pagi, dan sore harinya dinamakan SD Srengsengsawah III Petang. Sekarang bangunan tersebut menjadi sekretariat Resimen Mahasiswa (Menwa) Universitas Indonesia (UI).
Sebelah timur gedung SD, ada rumah Cang Munadi Rachman yang bertetangga dengan Kong Boda, beristrikan Nenek Buang.
Ke arah utara terdapatlah rumah Kong Haji Niih dengan kebun luas yang ditumbuhi pohon duren, rambutan, nangka, dan pohon-pohon keras lainnya. Berbatasan dengan Kong Haji Niih ada rumah Cang Haji Ali Ribu anaknya Kong Kenah. Disebut Ali Ribu karena ia orang kaya, uangnya ribuan. Sementara itu, warga Kampung Sawah, masih mengenal uang picisan, satuan terkecil sebelum rupiah, ratus, dan selanjutnya ribu.
Satuan jutaan apa lagi miliar, atau triliun, jarang bahkan tidak pernah terdengar.
Cang Haji Ali Ribu memiliki beberapa rumah, salah satunya dikontrak oleh Pak Njoman, tentara yang berasal dari Bali. Ke arah utara sedikit ada rumah Sapri, disusul rumah Niman Djoni dan Kong Djoni.
Namun untuk memudahkan saya akan menceritakan rumah-rumah penduduk yang kini sudah tidak tiada, patokannya saat ini adalah gerbang kedua pintu masuk UI. Setelah masyarakat Kampung Sawah menjadi korban penggusuran untuk pembangunan kampus Universitas Indonesia yang dimulai sejak 1975, rumah dan kebun saudara kita kena gusur sehingga terpaksa harus berpindah.
Umumnya warga pindah ke Kampung Sawah Sebrang Betan, yang kini tak lagi disebut begitu karena Sebrang Kulonnya sudah tidak ada. Ada juga pindah ke Pondok Cina Kukusan, Pondok Terong, dan Kampung lainnya.
Yang memprihatinkan adalah harga tanah ketika pembebasan yaitu hanya Rp700-Rp1.250 per m2, tergantung lokasinya. Namun para pemilik yang tanah luas, umumnya dibayar hanya Rp700 per m2. Jika satu keluarga memiliki tanah satu hektar, hanya mampu membeli 2.500 m2 di Seberang Betan, karena harga tanah di sini sudah meningkat menjadi Rp2.500 per m2.

Tentu mereka harus membangun rumah, maka tanahnya tinggal 1.500 m2. Bagi mereka yang ingin menunaikan ibadah haji, juga harus mengeluarkan biaya setara dengan tanah 1.000 m2. Jadi otomatis pemilik tanah 1 hektar, hanya tinggal 500 m2 yang dihuni oleh suami istri dan anak-anak yang mencapai 10 orang.
Kini, 40 tahun kemudian, mereka bertempat tinggal di pemukiman padat. Jelaslah bahwa penggusuran oleh pemerintah itu membuat orang Betawi di Kampung Sawah kehilangan tanah mereka. Namun ada juga cerita indah. Korban gusuran, kini menjadi guru besar di Fakultas Teknik UI, lantaran balas dendam. Sama seperti saya, ketika melanjutkan kuliah di UI ditanyakan alasan mengapa masuk kampus itu. “Saya balas dendam, ini kan kebon engkong saya.”
*) Ditulis oleh Lahyanto Nadie, Redaktur Khusus Indowork.id





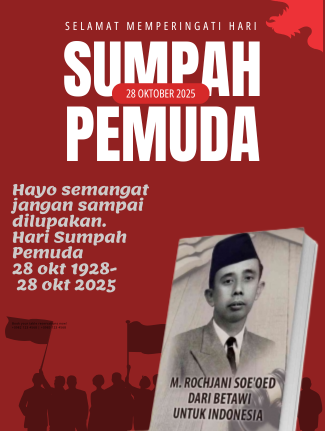








Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *