
INDOWORK.ID, JAKARTA: Saya menulis ini dengan penyesalan mendalam. Memerlukan sehari jeda untuk mempostingnya. Senin petang, 13 Oktober 2025, seharusnya saya ada di Teater Kecil, Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Akademi Jakarta, menghadiri acara penganugerahan penghargaan kebudayaan kepada tokoh yang saya kagumi: Martin Aleida .
Tapi entah kenapa saya ada di tempat lainnya. Undangan yang telah lama disimpan kadang lupa dibuka lagi – justru pada harinya tiba. Saya hanya bisa menyesali diri.
Selaku sastrawan, dalam kategori individu, Martin Aleida menerima penghargaan Akademi Jakarta yang bergengsi itu. Bersamanya hadir wakil dari Mama-Mama Masyarakat Adat Malind Anim dari Papua Selatan selaku penerima untuk kategori Komunitas.
Saya tak hadir di sana—meski undangan telah lama saya terima dan sudah saya niatkan untuk datang. Maka, saya menonton lewat rekaman siarannya di YouTube, dengan perasaan getir yang tak bisa sepenuhnya saya benarkan.
Yang membuat saya menyesal bukan sekadar absen dari sebuah acara penghargaan, melainkan karena saya mengenal Martin bukan hanya sebagai sastrawan besar, tetapi sebagai guru, ‘kyai’, ‘ajengan’, ‘pepunden’ – di bidang sastra dan jurnalisme; sosok manusia bersejarah yang hidupnya sepenuhnya dipersembahkan bagi kebenaran dan ingatan.
Ia tidak sekadar menulis kisah tentang peristiwa 1965; ia hidup di dalamnya, terseret di arusnya, dan bertahun – terluka yang tak kunjung sembuh. Ketika rekan rekan senasib mencoba melupakan dan menghapus trauma, menempuh kehidupan baru, Martin memilih untuk terus menulisnya. Ia menyalakan ingatan kolektif bangsa yang lama berusaha dipadamkan.
TULISAN SAYA DIBACA

Di usia 82 tahun, dengan kursi roda yang menemaninya, Martin hadir menerima penghargaan Senin petang itu dengan wajah teduh, dan senyum yang tidak menuntut apa pun.
“Saya hanya berharap tulisan saya dibaca,” katanya dalam sambutan. Kalimat sederhana itu sebetulnya adalah inti hidupnya.
Martin tidak lagi mengejar ketenaran, tidak berlari di antara panggung dan layar. Ia menulis dengan ketenangan orang yang tahu: satu-satunya cara agar bangsa ini tidak hilang arah adalah dengan mengingat apa yang pernah terjadi.
Saya masih ingat pertemuan kami bertahun lalu, di acara peluncuran novel Noorca N Massardi; “September”. Saya menyebut media saya dan Martin tersenyum dengan menyebut nama H. Thahar sebagai sahabatnya . Nama itu adalah boss saya di kantor. Selanjutnya begitu cepat kami menjadi karib. Saya selalu mengahadiri acara diskusi tentangnya tentang bukunya bahkan mengunjungi rumahnya di kawasan Pasar Minggu, Jakarta Selatan.
Dia bukan hanya penulis yang piawai, penyusun kata dan kalimat yang menghanyutkan namun juga pembicara yang rapi, runtut dengan aksen Sumatera Utaranya yang kental . ‘Sastrawan cum Wartawan’ asal Tanjung Balai ini sering berkata bahwa tugas penulis adalah menjaga agar kebenaran tak ikut mati. Dan ia melakukannya, dengan setia, meski tubuhnya menua dan sebagian kakinya kini telah terpangkas .
Penghargaan dari Akademi Jakarta untuknya terasa seperti penebusan yang tertunda. Sebab, pada 2013 penghargaan yang sama sempat dibatalkan — meninggalkan luka simbolik dalam dunia sastra Indonesia. Tapi seperti kata Zeffry Alkatiri sore itu, “Rezeki tidak akan tertukar, hanya tertunda.”
Tahun ini, penghargaan itu akhirnya datang juga—sebagai bentuk pengakuan dan juga pengingat bagi kita semua bahwa keberanian menulis tentang kebenaran adalah bentuk paling tinggi dari kesetiaan pada kemanusiaan.
MENULIS DI RUANG SEPI

MARTIN menulis dari ruang sepi, di rumahnya sambil menemani isterinya yang mengidap dimensia. Sambil menulis, dia harus memasak untuk isterinya juga. “Saya melarang dia menyalakan kompor karena sering lupa mematikannya, ” katanya. Dua kali dia ditinggalkan di rumah sakit. Mendadak isterinya menghilang begitu saja.
Sri Sulasmi yang dimensia itu pada Oktober 1965 adalah perempuan cantik yang dipujanya, yang di kantung kemejanya terselip secarik surat cinta saat dia ditangkap aparat “Operasi Kalong” yang menjebloskan ke tahanan Kodim O5O1 Jakarta Pusat (kini gedung Indosat.pen).
Berdua mereka menjadi penghuni, melewati hari hari kelam, menyaksikan tahanan lain diinterogasi, disiksa dan dipecut dengan duri ikan pari – dipaksa mengaku sebagai PKI dan pembunuh para jendral dan menunjukkan teman teman lainnya yang lari.
“Tugas Sri membersihkan darah yang tercecer di lantai, ” kenangnya. Sri Sulasmi kemudian menjadi pasangan hidupnya hingga usianya 82 kini.
Setahun dalam penjara Kodim 0501 tanpa pengadilan Martin dibebaskan begitu saja. “Dan saya masuk ke penjara lebih besar lagi, yaitu masyarakat yang antipati dan memberikan stigma kejam pada PKI, ” katanya.
Ia mengganti nama aslinya. Tapi terus bersuara lewat tulisan mewakili mereka yang dibungkam oleh sejarah, memberi nama pada yang dilupakan, memberi wajah pada mereka yang hanya disebut “korban.”
Dalam karya-karyanya, kita membaca luka yang bukan hanya miliknya, melainkan luka bangsa. Dan dari sana, kita belajar bahwa mengingat adalah tindakan moral.

KETUA Akademi Jakarta Seno Gumira Ajidarma dalam kata sambutannya itu berkata, “Penghargaan ini adalah penanda—tentang siapa yang harus dibela dan diperjuangkan, serta ujian apakah kita sungguh masih sebangsa dan setanah air.”
“Karena di tengah negara yang makin pandai melupakan, Martin dan Mama-Mama Malind Anim adalah dua kutub ingatan yang menegakkan kemanusiaan: satu lewat tulisan, satu lewat tanah,” ungkapnya.
Dan saya, yang lupa hadir di petang hari itu, belajar lagi satu hal penting : bahwa melupakan bukan hanya kelalaian, tapi juga kehilangan bagian dari diri kita sendiri.
Maafkan atas kelalian saya, Pak Martin . Semoga di kesempatan berikutnya, saya tidak lagi absen. Dan semoga bangsa ini pun tidak absen dari upaya mengingat orang-orang yang membuat kita tetap manusia.
Ditulis oleh Dimas Supriyanto, Founder Jakarta Weltevreden
Foto foto : Noorca NM





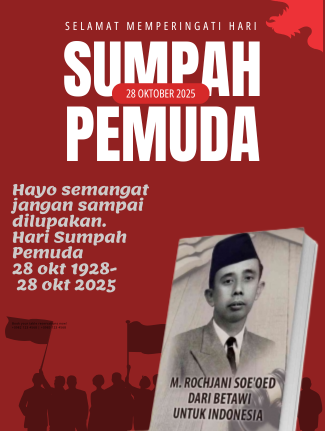




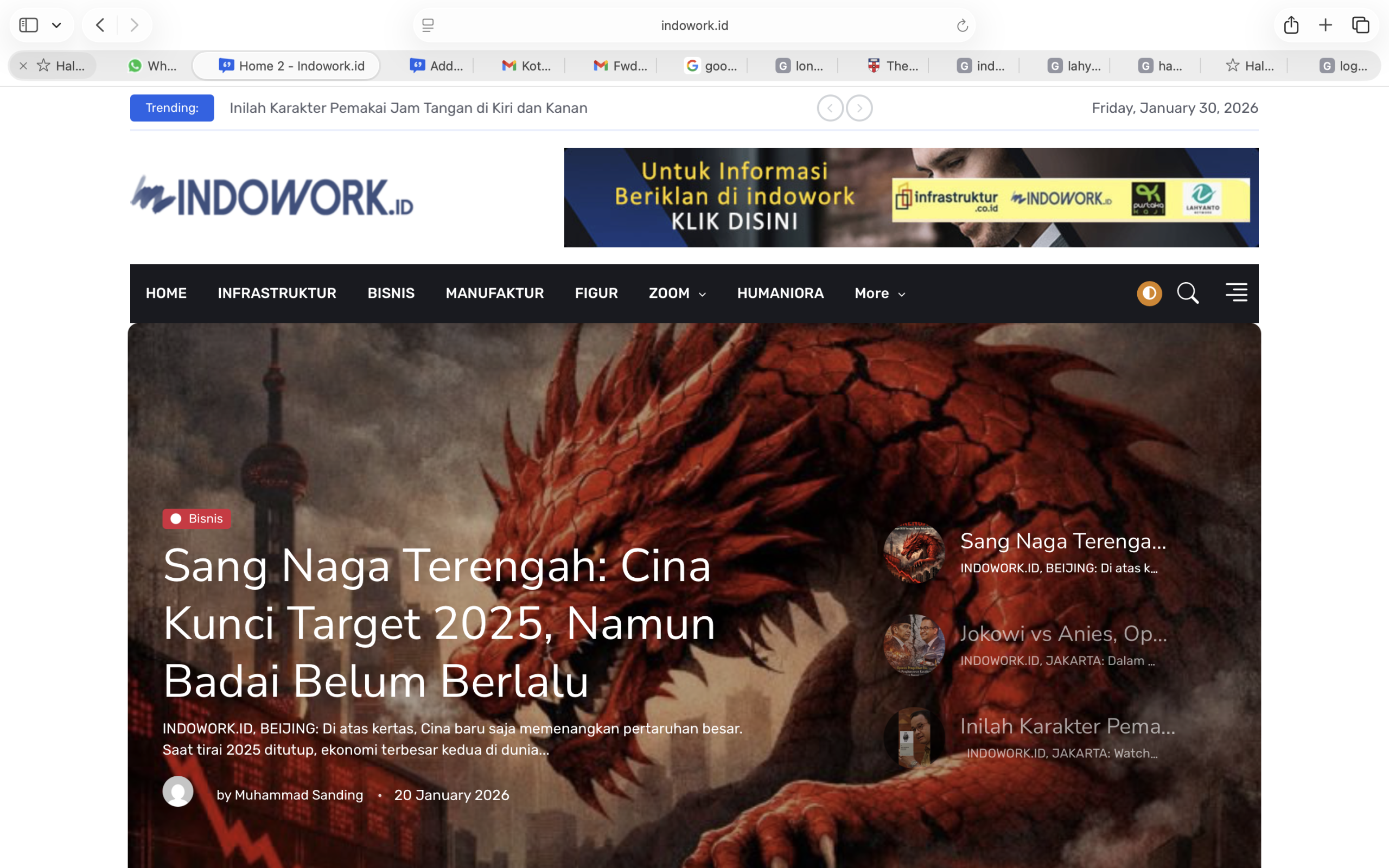



Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *