Kondisi Pascaperang, Momentum Perkembangan Alat Berat

INDOWORK.ID, JAKARTA: Kondisi pascaperang yang porak poranda menimbulkan kebutuhan akan pembangunan meningkat drastis. Teknologi alat berat dengan sistem hidraulik segera menemukan momentum perkembangannya. Jenis alat berat juga makin beragam: ada wheel loader untuk memuat material, motor grader untuk meratakan jalan, dump truck untuk mengangkut hasil tambang, dan crane untuk mengangkat beban tinggi. Pembangunan kota, industri, dan infrastruktur di seluruh dunia tak bisa lepas dari kontribusi alat-alat ini.
Sejarah pra industri alat berat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari era kolonial, khususnya masa penjajahan Belanda dan Jepang. Pemakaian alat-alat berat di masa itu tujuannya masih sangat terbatas dan sederhana. Seperti untuk pertanian, perkebunan, pembangunan jembatan, jalan, bendungan, dan pelabuhan.
Alat-alat berat itu banyak didatangkan dari Eropa. Selain membantu pengerjaan proyek besar seperti pengerjaan jembatan, bendungan, dan pelabuhan. Pemerintah Hindia Belanda saat itu juga mendirikan semacam bengkel untuk pemeliharaan dan perawatan persenjataan dan alat berat.

Rudolf Mrazek dalam buku Engineer of Happy Land berdasarkan surat kabar De Ingenieur in NI volume 6 nomor 2 (Februari 1939) pada tahun itu sudah terdapat alat berat berupa truk yang menyerupai dump truck sebanyak 12.860 unit. Dari puluhan ribu truk yang ada di Hindia Belanda tersebut, sebagian di antaranya bermerek Chevrolet.
Bekas Kapten pasukan khusus KNIL Belanda Raymond Paul Pierre Westerling adalah orang yang paling banyak menggunakan alat berat tersebut untuk jasa angkutan perkebunan. Dalam buku Westerling de Eenling (1982) yang ditulis Dominique Venner dan autobiografinya Challenge to Terror (1953) dia menjuluki armadanya dengan “Truk Westerling” sebagai kendaraan pengangkut.
Selain itu, ada juga transport onderneming Her Galaxina seperti Bintang Tiga, Selecta, dan Ie Hian yang juga ikut meminjamkan kendaraan pengangkut. Keberadaan truk sebagai kendaraan pengangkut fungsi utamanya adalah untuk kebutuhan pergerakan militer, namun di luar itu ada kepentingan bisnis untuk mengangkut barang dagangan.
Saat peralihan kekuasaan dari Belanda ke Jepang pada 1942, negara asal pemakaian alat besar pun berganti. Sejumlah alat berat dari negeri Matahari Terbit giliran mendominasi hingga Indonesia meraih kemerdekaan pada 1945.
Praktis, pemakaian alat-alat berat dari luar negeri di Indonesia turut mewarnai sejumlah program pembangunan di Indonesia pasca merdeka (1945-1970).
Pada 1965 (Orde Lama): Urusan kendaraan alat berat berada di bawah koordinasi Departemen Perhubungan dengan dasar Undang-undang Pokok Lalu Lintas Darat
Pada Pasal 1 Ayat (1) Sub B yang mengatur:
Kendaraan bermotor. Dengan adanya anak kalimat “selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel” maka ketentuan-ketentuan terhadap kendaraan bermotor tidak berlaku terhadap alat angkutan yang bergerak diatas rel, seperti lokomotif dan sebagainya (bandingkan dengan penjelasan ayat (2).
Semua kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik termasuk dalam istilah ini, baik yang merupakan mesin uap, motor pembakar ataupun motor listrik.
Peralatan teknik, yang menggerakkan kendaraan itu harus berada pada kendaraan itu. Dengan demikian kereta gandengan atau tempelan tidak dianggap sebagai kendaraan bermotor.
Otobus listrik (trolley bus), walaupun sumber tenaganya berada di pusat pembangkit listrik tetapi oleh karena peralatan teknik yang diperlukan untuk menggerakkan kendaraan tersebut berada pada kendaraan, maka trolley bus termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor.
Pada 1967-1973, Urusan kendaraan alat berat berada di bawah koordinasi Departemen Pekerjaan Umum karena banyak proyek infrastruktur dan pembangunan memerlukan alat berat.
LANCARKAN BISNIS ALAT BERAT
Pada 1968, pemerintah mengeluarkan ketentuan tentang Twin Unit Packing atau SKD, sekadar untuk mulai melancarkan bisnis alat berat, yang waktu itu boleh dikatakan baru dirintis. Ketentuan tersebut memperbolehkan impor dalam keadaan terurai dan dikemas dalam satu kemasan, yang masing-masing berisi dua unit. Proses selanjutnya tinggal mencat dan memasangnya menjadi unit jadi dengan obeng dan kunci, tanpa pengelasan.
Secara regulasi, importasi alat-alat berat di Indonesia resmi diatur di Indonesia sesuai regulasi pada 1970. Melalui Keputusan Menteri Perdagangan RI No. 315/KP/XII/1970 yang diteken 4 Desember 1970. Didahului oleh Kepres No.260 tahun 1967 yang menunjuk Departemen Perdagangan yang mengatur regulasi tentang impor dan ekspor barang.
Aturan turunannya, Departemen Perdagangan menerbitkan SK 315/1970 yang mengatur impor alat-alat berat (khusus pemindah tanah dan pembangunan jalan) termasuk layanan purna jual dan penyediaan suku cadang hanya boleh diberikan izin kepada perusahaan nasional lokal yang menyelenggarakan keagenan tunggal merek tertentu.
Dalam dunia industri alat berat di Indonesia, status sebagai agen tunggal pemegang merek (ATPM) telah diatur. Keputusan Menteri Perdagangan No. 330/KP/XII/1970 menetapkan sejumlah kriteria ketat yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang ingin menjadi agen tunggal alat berat dari luar negeri.
Pertama, perusahaan tersebut harus berstatus sebagai perusahaan nasional, yang bisa berasal dari sektor swasta maupun milik negara. Artinya, entitas asing tidak dapat langsung menguasai peran strategis ini tanpa melalui kemitraan dengan pihak lokal.
Selanjutnya, perusahaan harus memiliki tenaga ahli di bidang alat berat yang bersertifikat resmi dari Kementerian Perindustrian. Ini untuk memastikan bahwa agen tunggal tidak hanya menjual produk, tetapi juga mampu memahami aspek teknis dan operasional dari alat berat tersebut.
Selain itu, keagenan ini harus didukung oleh perjanjian kontraktual yang sah dengan produsen alat berat di luar negeri, yang menunjuk perusahaan tersebut sebagai satu-satunya representasi resmi di Indonesia. Terakhir, perusahaan wajib memiliki fasilitas layanan purna jual—baik dari sisi suku cadang maupun perawatan teknis—untuk menjamin keberlangsungan operasional alat berat di lapangan.
Ketentuan ini dirancang untuk melindungi ekosistem industri dalam negeri sekaligus menjamin mutu layanan bagi pengguna alat berat, khususnya di sektor konstruksi, pertambangan, dan kehutanan. Dengan sistem keagenan tunggal yang terkontrol, pemerintah ingin mencegah persaingan tidak sehat antarimportir dan memastikan transfer pengetahuan serta teknologi bisa terjadi secara berkelanjutan kepada pihak lokal.
Di tengah meningkatnya permintaan alat berat akibat proyek infrastruktur nasional, peran agen tunggal yang profesional dan berstandar tinggi menjadi semakin krusial.
Untuk dapat izin importasi alat berat, Dirjen Perdagangan menerbitkan SK No. 0231/DPP/3/III/1971 berisikan peraturan importasi alat berat hanya dapat dilakukan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).
Pada 1972 dikeluarkan ketentuan mengenai impor unit dalam keadaan terurai penuh (complete knocked-down/CKD), yang mengharuskan impor alat berat dalam keadaan terurai penuh (CKD). Proses di dalam negeri selanjutnya adalah menyetel, mengelas, mencat, dan memasang menjadi unit jadi. Proses penyetelan, pengelasan, pengecetan, dan pemasangan tersebut secara keseluruhan disebut perakitan.
Ketentuan CKD pada waktu itu dirumuskan berdasarkan pengalaman di waktu lampau dalam pengimporan unit pada kendaraan otomotif dari General Motor dan Chrysler, berturut-turut oleh PT Gajah Motor dan PT Indonesia Service Company.
Namun, yang khusus adalah, bahwa ketentuan CKD tersebut harus dilakukan dengan sistem album, yang memuat foto-foto dari masing-masing komponen yang harus diimpor. Eks dirjen Industri Logam Dasar Ir Suhartoyo menyatakan bahwa di dunia hanya Indonesia yang memakai sistem album tersebut, setidak-tidaknya waktu itu kita tidak meniru dari mana pun dalam menentukan cara tersebut.
Pertimbangan waktu itu adalah agar pelaksanaan dan pengawasan ketentuan tersebut, baik di pabrik maupun di pelabuhan, dapat dilakukan oleh pengusaha-pengusaha dan pejabat-pejabat yang bersangkutan secara visual, sesuai dengan kemampuan pemahaman segi-segi administratif dan ketelitian pada waktu itu. Dengan sendirinya, dalam keadaan lebih menguntungkan, sistem CKD dapat dengan lebih mudah dan sederhana dilakukan, dengan penentuan nomor-nomor seri dari masing-masing komponen.
Pada waktu itu juga mulai diberlakukan sistem agen tunggal atau pemegang merek untuk impor alat berat. Perusahaan perakitan ditunjuk berdasarkan fasilitas yang telah ada sebelumnya. Usaha perakitan dan agen tunggal harus dipisahkan untuk mendorong dan membuktikan, bahwa usaha perakitan merupakan kegiatan yang secara ekonomis dapat dipertanggungjawabkan.
Sebelum itu (lebih-lebih di zaman Orla), bisnis alat berat mengambil untung dari permainan perbedaan kurs valuta asing (yang dikontrol dan dialokasi oleh pemerintah) dengan rupiah. Kegiatan perakitan disubsidi oleh usaha perdagangan, sehingga tidak pernah mencapai tingkat ekonomis yang menguntungkan, dengan akibat, tidak ada dorongan untuk bekerja lebih baik dan menghasilkan produk dengan kualitas yang memuaskan, atau bekerja asal jadi.
Pada 1973, Direktorat Jenderal Perindustrian Dasar memperjelas definisi mengenai alat-alat berat dalam konteks regulasi industri dan kebijakan importasi. Dalam penjelasan tersebut, alat-alat berat diklasifikasikan ke dalam empat sektor utama, yakni peralatan konstruksi, peralatan pertambangan, peralatan industri, dan peralatan pertanian.
Klasifikasi ini bertujuan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai jenis-jenis mesin dan peralatan yang termasuk dalam kategori alat berat, sehingga memudahkan proses pengawasan, perizinan, dan pengembangan industri penunjangnya di dalam negeri.
Di era ini, sejumlah importir Indonesia, seperti United Tractors (UT) telah melakukan beberapa importasi alat berat. Untuk diketahui, UT sebelumnya adalah Divisi Alat Berat Astra yang berdiri pada 1969. Alat berat pertama yang berhasil mereka jual adalah excavator merek Hymac yang dibeli oleh Dinas Pekerjaan Umum Palembang. Sumatera Selatan, yang dikapalkan langsung dari Singapura menuju Palembang.
KERJA SAMA DENGAN ALLIS CHALMERS
Selanjutnya, mereka bekerjasama dengan Allis Chalmers, yaitu salah satu pemain besar di industri ini bersama Hydraulic Machinery, International Harvester, dan Nomad. Pada waktu itu industri alat berat dunia memang didominasi oleh produk Amerika dan Eropa.
Sementara itu, Traktor Nasional yang mendapatkan dukungan dari Tractor Malaysia, melakukan kerja sama impor alat berat merek Caterpillar. Pasar alat berat pun bergairah.
Pada era 1970, terjadi suatu perubahan dalam landskap industri alat berat. Allis Chalmers yang tadinya berada pada Divisi Alat Berat Astra, beralih ke PT Altrak, bagian dari BERCA Group milik Moerdaya Poo. Kemudian, keagenan Caterpillar yang tadinya dipegang Traktor Nasional, beralih ke PT Trakindo Utama, perusahaan milik AHK Hamami. Sementara Traktor Nasional sempat menjadi distributor Komatsu sebelum akhirnya mendarat ke United Tractors.
Sebagai catatan, perkiraan unit alat berat yang didatangkan para importir ke Tanah Air pada periode 1970 hingga 1980 berkisar 1.000 hingga 2000-an unit/tahun.
Babak selanjutnya, pada tahun 1980, Direktorat Jenderal Industri Logam Dasar Departemen Perindustrian mendorong pengembangan alat berat menjadi industri alat berat dalam negeri dengan potensi pasar alat berat di Indonesia diperkirakan mencapai 5.000 unit/tahun dalam tempo 5 tahun ke depan (1985).
Untuk mendorong pengembangan alat berat menjadi industry heavy equipment di dalam negeri itulah, pada akhir 1980, Dirjen Industri Logam Dasar Departemen Perindustrian memutuskan mengembangkan alat berat menjadi industri. Pemerintah meminta sejumlah agen importir alat berat bersama para principalnya mengajukan proposal kesiapan membangun industri alat berat di Indonesia. Di antaranya United Tractors dan Komatsu, Trakindo Utama dan Caterpillar. Sejak saat itu, mulailah era baru alat berat memasuki masa industri di Indonesia.

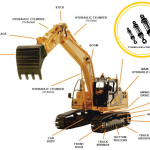



Leave a reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *